Dulu aku pikir jadi orang tua itu kayak punya startup.
Serius. Ada rencana jangka pendek, jangka panjang, target, evaluasi, sampai strategi pengembangan.
Bedanya, yang aku “kelola” bukan produk, tapi manusia kecil yang katanya “harus sukses di masa depan”.
Setiap hari, pikiranku dipenuhi to-do list:
daftar sekolah terbaik, les musik, les bahasa, les sains, bahkan les kepercayaan diri.
Pokoknya semua yang bisa membuat anakku terlihat “siap bersaing”.
Karena, hei, dunia sekarang keras, kan?
Tapi semakin aku sibuk mengatur jadwal dan membandingkan pencapaian,
semakin sering aku menemukan diriku di depan laptop tengah malam, lelah, dan tiba-tiba nangis.
Nangis karena sadar, semua “ambisi baik” itu kadang terasa seperti beban.
Buat aku, dan buat dia anakku sendiri.
Suatu hari, aku pulang kantor dengan wajah kusut.
Di rumah, anakku sedang mengerjakan tugas sekolah.
Di meja belajarnya, aku lihat tumpukan buku warna-warni, beberapa lembar tugas yang belum selesai, dan segelas susu yang udah dingin.
“Gimana tugasnya?” tanyaku.
Dia ngangguk pelan, tapi suaranya lirih.
> “Bu, aku capek. Boleh gak besok gak ikut les dulu?”
Jujur, kalimat itu sederhana. Tapi nadanya bikin aku berhenti total.
Aku lihat matanya. Ada lingkar hitam halus di bawahnya anak umur 8 tahun yang harusnya masih main petak umpet, bukan mikirin nilai dan target.
Aku gak langsung jawab.
Cuma diem, dan dalam hati aku bertanya:
“Selama ini siapa sih yang aku kejar? Kesuksesan dia, atau validasi aku sebagai orang tua?”
Masalahnya, jadi orang tua di zaman sekarang tuh kayak ikut lomba marathon di TikTok.
Semua orang update progres anaknya:
anaknya udah bisa baca, bisa nari, bisa coding, bisa ikut lomba ini itu.
Kadang cuma scroll lima menit aja udah cukup buat bikin perasaan minder.
Kok anak orang lain serajin itu, seaktif itu, seberprestasi itu?
Lalu, mulai deh rasa bersalah itu muncul:
“Jangan-jangan aku kurang ngajarin dia.”
“Jangan-jangan aku terlalu santai.”
“Jangan-jangan aku ibu yang gagal.”
Padahal, siapa sih yang nyuruh kita jadi sempurna?
Siapa juga yang bilang anak harus selalu unggul biar layak dibilang “hasil didikan yang baik”?
Aku pernah baca kalimat yang nancep banget:
> “Anak bukan miniatur dari ambisi orang tua.”
Dan ya, bener banget.
Kadang kita ingin anak punya apa yang dulu gak kita punya.
Tapi lupa, mungkin dia gak butuh itu.
Mungkin yang dia butuh cuma waktu main bareng, pelukan, atau sekadar ditemani tanpa kita sibuk nge-scroll ponsel.
Aku jadi ingat masa kecilku sendiri.
Orang tuaku gak pernah nyuruh aku ikut les ini itu.
Gak ada jadwal padat, gak ada “prestasi” yang harus diraih tiap minggu.
Tapi aku ingat satu hal: mereka hadir.
Setiap kali aku pulang sekolah, mereka tanya “gimana harimu?” bukan “dapet nilai berapa?”.
Mungkin itu yang hilang dari banyak orang tua zaman sekarang, termasuk aku.
Kita terlalu sibuk membentuk masa depan, sampai lupa menikmati masa sekarang.
Kadang aku mikir, dunia ini makin cepat, tapi hati kita malah makin lambat menyadari esensinya.
Kita ingin anak tumbuh jadi versi terbaik, tapi lupa bahwa “tumbuh” itu butuh ruang untuk salah.
Butuh waktu untuk istirahat.
Butuh kesempatan untuk gagal tanpa dihakimi.
Kita bilang “anak harus kuat”, tapi sering lupa ngajarin cara istirahat.
Kita bilang “anak harus tangguh”, tapi jarang menunjukkan cara minta tolong.
Kita bilang “anak harus sopan”, tapi kadang kita sendiri ngomong ke mereka sambil marah.
Dan ironisnya, kita nyuruh anak bahagia, tapi kita sendiri kelihatan gak bahagia.
Kita pengin mereka percaya diri, tapi setiap hari kita insecure sama diri sendiri.
Ternyata, anak gak butuh orang tua yang sempurna — cukup orang tua yang sadar bahwa mereka juga manusia yang sedang belajar.
Sekarang, setiap kali aku mulai panik mikirin perkembangan anakku,
aku belajar untuk berhenti sejenak.
Aku lihat dia lagi main lego, nyengir sendiri, kadang jatuhin potongan kecil lalu ketawa.
Dan aku sadar, mungkin di situ letak kebahagiaan yang sesungguhnya sederhana, tapi nyata.
Aku gak perlu punya anak yang selalu juara kelas.
Gak harus anakku yang paling disiplin, paling pintar, paling cepat.
Cukup dia tumbuh dengan hati yang tenang dan tahu bahwa rumah adalah tempat paling aman untuk jadi diri sendiri.
Karena sejatinya, yang kita rawat bukan prestasi, tapi jiwa.
Yang kita bentuk bukan ranking, tapi karakter.
Yang kita jaga bukan citra keluarga di depan orang lain, tapi rasa percaya di dalam rumah sendiri.
Sekarang, kalau ada yang nanya,
> “Anakmu udah bisa apa aja?”
Aku jawab pelan sambil senyum,
> “Dia lagi belajar jadi dirinya sendiri. Dan aku juga.”
Karena ternyata, parenting bukan tentang siapa yang paling cepat ngajarin,
tapi siapa yang paling sabar menemani.
Bukan tentang berapa banyak les, tapi seberapa sering kita hadir.
Bukan tentang mencetak “anak hebat”, tapi tentang membesarkan manusia kecil yang tahu bahwa dirinya dicintai apa adanya.
Kadang aku masih merasa gagal. Masih marah, masih bingung, masih takut salah langkah.
Tapi setiap kali anakku memeluk dan bilang,
> “Ibu, aku sayang Ibu,”
semua teori parenting mendadak gak penting lagi.
Karena ternyata, yang paling dibutuhkan anak bukan orang tua yang tahu segalanya,
tapi orang tua yang mau dengerin, minta maaf, dan terus belajar.
Dan malam itu, sebelum tidur, aku lihat wajahnya yang damai.
Di antara napas kecilnya, aku bisikkan dalam hati:
> “Maaf ya, Nak. Kadang Ibu terlalu sibuk membentuk kamu jadi seseorang.
Padahal kamu cuma butuh Ibu yang ada.
Kamu bukan proyek, kamu titipan.
Dan Ibu akan belajar terus, supaya bisa menjagamu dengan lebih baik, bukan dengan target, tapi dengan cinta.”
✨ Karena pada akhirnya, menjadi orang tua bukan tentang mencetak generasi unggul.
Tapi tentang belajar mencintai tanpa syarat dan tumbuh bersama, tanpa paksaan.
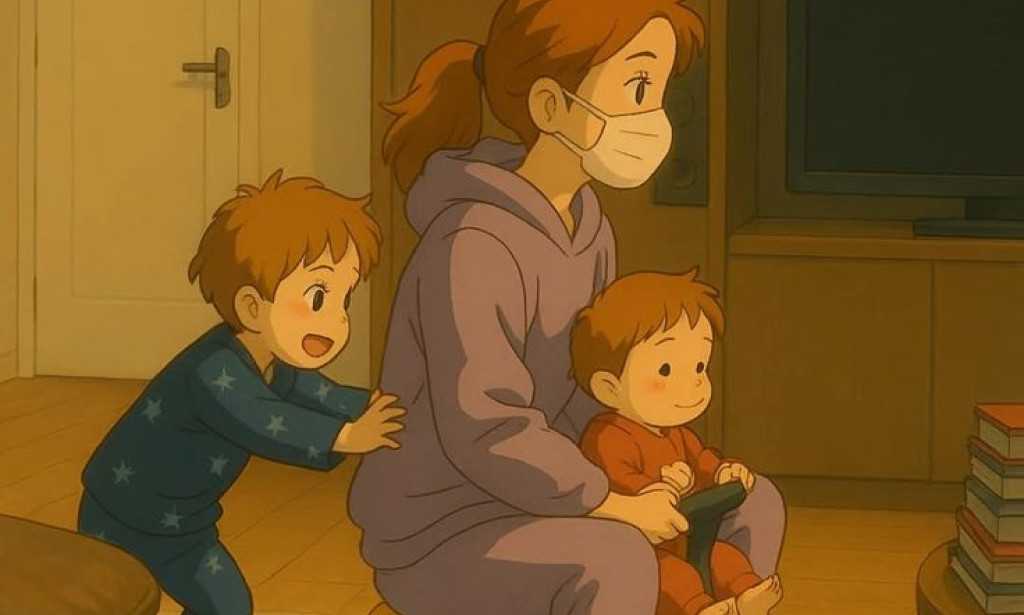

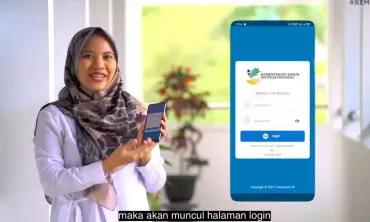




Komentar
Silakan login untuk berkomentar.