Ada masa di mana “adab” jadi tren baru.
Orang-orang mulai bicara soal sopan santun, etika, dan budi pekerti di media sosial—lengkap dengan caption bijak dan baju seragam warna earth tone.
Tapi di antara semua itu, ada satu pertanyaan kecil yang menggelitik:
Apakah adab masih punya makna, atau cuma jadi gaya?
Zaman sekarang, adab bisa dipamerin lewat video.
Ada yang bikin konten sedang “menyimak guru dengan khusyuk”, ada juga yang menulis caption panjang tentang pentingnya menghormati orang tua sambil menandai produk skincare di bawahnya.
Tidak salah, tentu saja. Tapi lucu aja, karena kadang kita terlalu sibuk menunjukkan adab sampai lupa menghidupinya.
Aku pernah lihat satu video: seorang remaja menunduk sopan di depan gurunya. Cantik banget adegannya, slow motion, background lagu sendu.
Tapi di kolom komentar, ia membalas kritik netizen dengan nada tinggi.
Dan aku pikir, “Mungkin adab memang mudah dipelajari, tapi sulit diterapkan saat tak ada kamera.”
Dulu, adab itu sesuatu yang kita pelajari dari keseharian.
Dari cara kita minta maaf tanpa gengsi.
Dari bagaimana kita mendengarkan orang lain, bahkan ketika kita gak sepakat.
Dari kebiasaan menutup mulut saat menguap, mengucapkan terima kasih, dan menepuk bahu teman yang sedih tanpa perlu unggahan story.
Tapi sekarang, dunia digital bikin kita lebih sering mementingkan citra daripada rasa.
Adab jadi semacam kostum sosial—dipakai saat dilihat orang, dilepas saat tak ada penonton.
Ada yang bilang, generasi sekarang kehilangan adab.
Padahal mungkin bukan hilang, cuma bentuknya berubah.
Kita lebih berani ngomong di depan umum, tapi sering lupa cara diam dengan sopan.
Kita jago membela kebenaran, tapi lupa menyampaikannya dengan lembut.
Kita peka sama isu moral di media, tapi tumpul terhadap perasaan orang terdekat.
Mungkin ini bukan soal kurang ajar, tapi terlalu banyak distraksi.
Terlalu sibuk membangun persona baik sampai lupa menjadi manusia baik.
Aku jadi ingat, dulu ibuku pernah bilang begini waktu aku kecil:
> “Nak, adab itu bukan soal cara kamu menunduk, tapi cara kamu menghargai orang yang berbeda.”
Dan aku baru paham artinya sekarang.
Bahwa adab bukan cuma tentang gesture, tapi tentang niat.
Bukan soal seberapa pelan kamu bicara, tapi seberapa dalam kamu mendengar.
Bukan tentang berapa kali kamu bilang ‘terima kasih’, tapi seberapa tulus kamu mengucapkannya.
Lucunya, di era ini, kita bisa tampak beradab tanpa benar-benar beradab.
Kita bisa mengetik “maaf ya, kak 🙏” sambil jari kita gemetar karena emosi.
Kita bisa mengutip kata bijak dari tokoh besar, padahal baru saja memotong pembicaraan teman.
Kita bisa menulis status tentang kesabaran, tapi meledak hanya karena antrean terlalu panjang.
Dan aku gak menulis ini buat menyindir siapa pun, karena jujur saja, aku juga sering begitu.
Kadang, aku lebih sibuk terlihat “baik” di mata orang lain daripada benar-benar berbuat baik.
Mungkin kita semua sedang belajar.
Belajar menyeimbangkan antara dunia nyata dan dunia maya, antara citra dan hati.
Belajar bahwa adab bukan untuk dinilai, tapi dijalani.
Bahwa rasa hormat bukan cuma untuk mereka yang di atas kita, tapi juga untuk siapa pun bahkan yang tidak sependapat dengan kita.
Karena pada akhirnya, adab itu bukan tentang siapa yang paling lembut bicaranya,
tapi siapa yang paling rendah hatinya.
Sekarang, tiap kali aku lihat perdebatan di media sosial tentang “siapa yang paling beradab”, aku cuma senyum kecil.
Karena mungkin, orang yang benar-benar beradab justru tidak ikut adu argumen.
Dia diam, mengamati, dan memilih untuk tetap menghormati — bahkan ketika orang lain tidak.y
> Dunia mungkin butuh lebih sedikit orang yang bicara soal adab,
dan lebih banyak orang yang mencontohkannya.
Dan mungkin, kalau kita mulai dari situ,tanpa label, tanpa gaya, tanpa kamera.
adab akan kembali jadi sesuatu yang sederhana:
rasa hormat yang tumbuh dari hati.
🕊️ Catatan kecil:
Adab gak butuh panggung. Ia cuma butuh ruang kecil di hati, tempat kita belajar rendah, belajar mendengar, dan belajar menghargai — bahkan yang berbeda dari kita.


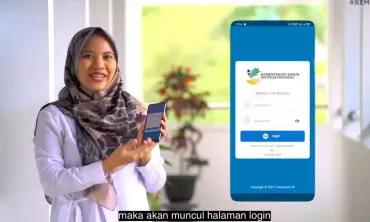




Komentar
Silakan login untuk berkomentar.